Malam senin tahun 2011 di entah pada tanggal berapa, aku tidak ingat persis kapan itu terjadi. aku sowan Kyaiku, dari komplek C aku berangkat, jam sudah menunjuk hampir tengah malam, begitu ada teman memberitahuku bahwa Kyai sedang menemui tamu dengan pintu terbuka, aku bergegas menuju ndalem dengan semangat yang bergejolak. Kulihat dari luar ada tiga tamu, di Ndalem sederhana bercat hijau tua itu, beliau biasa melayani tamu-tamu yang berdatangan dari tingkat apapun, aku mulai masuk melalui pintu depan yang setengah terbuka itu, sambil merundukkan badan aku mengucap salam. Santri Al-Fadlu seusia atau sedikit di atasku, acap kali heran dengan keberanianku yang nampak terasa tidak punya beban setiap sowan kepada beliau, minta wejangan, atau tibatiba menyelusup ke dalam ketika ada tamu untuk nguping penuturan Kyai, atau sekadar ngalap berkah dengan cara mengecup punggung tangannya.
Aku selalu bilang kepada mereka bahwa sowan adalah tindakan membuka ruang untuk bisa lebih dikenal, agar namaku benar-benar nancap di hati Kyai, dengan begitu akan ada potensi lebih besar kalau di setiap doanya namaku disertakan secara khusus. Mungkin ini hanya salah satu jalan untuk menuju ke sana, bahwa para santri kebanyakan sepakat kalau ada santri dipanggil Kyainya dengan menggunakan nama aslinya, maka nyaris bisa dipastikan kalau santri itu bukan sembarang orang. meski aku tahu bahwa tanpa di kenal pun, Kyai akan selalu mendoakan para santrinya. Di antara buktinya adalah bahwa setiap Istighosah yang di adakan tiap malam jum'at kliwon itu, Kyai sering mendahulukan doa untuk santrinya dibanding yang lain. Yang demikian sudah menjadi konsumsi publik kalau bahwa Kyai lebih menitik-beratkan tanggung jawab sebagai Kyai kepada santrinya ketimbang Abah kepada Putraputranya.
Hanya sedikit yang bisa mencapai derajat dimana namanya dipanggil oleh Kyai, ada satu kebanggaan tersendiri, sejauh ini, hanya beberapa santri senior yang mendapatkan itu. Meski ada juga yang dikenal Kyai secara khusus karena saking nakalnya. Untuk mencapai derajat tersebut aku punya cara sendiri, yaitu sowan. Ya, aku punya hobi sowan ke Kyai. Tapi malam itu, tanpa bermaksud apaapa, aku sowan dengan niatan ingin mengadukan satu persoalan. Dan sowan adalah bukan tujuan, tapi alat untuk menuju tujuan, seperti halnya salaman dengan Kyai, tindakan salaman itu bukan merupakan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan, begitu pula, Kyai mengenal dan hafal nama salah satu santri itu sebenarnya bukan tujuanku. Di antara hal yang berkait-paut dengan itu hanya sebagai jalan, bukan tujuan, yang menjadi tujuanku sejauh itu dalam bertindak adalah agar mendapat lubernya berkah, sowan itu yang nampaknya menjadi caraku untuk menuju sana, bahwa semakin sering sowan, ia akan mendapat pengalaman spritual dalam bentuk lain, harapanku selanjutnya ketika sudah sering sowan, adalah agar dikenal namaku, sehingga dengan begitu namaku akan mendapat kesempatan besar untuk disebut, sementara aku meyakini bahwa setiap sesuatu yang didawuhkan oleh Kyai itu mengandung unsur doa. Dengan demikian, peluang untuk mendapat berkah kian banyak sejalan dengan nama yang disebut dalam doa Kyai. Sebab itulah aku menggunakan sowan sebagai jalan untuk menuju sana.
Kebanyakan para santri terlalu ringkih terhadap sikap Kyai yang lebih menunjukkan ke-tegasan, aku justru heran kepada santri yang menyampaikan ketakutannya setiap berhadapan dengan Kyai, menurutku, secara implisit, tanpa mengesampingkan nilai ke-tawadzu'an seorang santri kepada Kyainya, itu sudah keterlaluan, padahal pengalamanku sejauh ini setiap sowan, Kyai selalu membuka peluang untuk bisa diteladani secara diamdiam, maksudnya, melalui perilaku itulah Kyai mengajarkan. Para santri pada umumnya salah kaprah bahwa kebijaksanaan dipahami sebagai kekerasan sikap, ketegasan dimaknai sebagai kemarahan. Yang demikian membuat para santri terlanjur membiarkan kesalahan dalam menafsir sikap, sehingga itu Kyai dikesankan dengan kekerasan.
Kebijaksanaan Kyaiku nampak setiap ada santri yang sowan, sikap kasih-sayangnya justru tertutup oleh sifat ke-tegasan beliau, aku pernah mendapati seorang teman yang sowan, karena kegugupan-nya ketika menyampaikan sesuatu, menjadikan beliau menampilkan peraupan yang berbeda. Ceritanya, ada teman se-kamar, namanya Aniq. Dia menyowankan teman yang sakit untuk pulang, penyampaiannya yang gugup itu membuat Aniq ditampar dengan sandal, meski pada akhirnya diizinkan. Hal itu menjadi lelucon bahwa dua tahun selepas kejadian itu--yang selanjutnya dikenal dengan Tragedi Sandal Carvil, Aniq hafal Al-Quran. Aku menimpali, padahal itu baru sandal carvil, mungkin saja kalau ditampar dengan sandal bakiak Aniq hafal Tafsir Jalalain berikut Showi-nya
Oleh mayoritas yang kenal Kyaiku, mereka memanggilnya dengan sebutan Abah. Tak terkecuali aku. Mungkin sebutan Abah itu terkesan lebih akrab dibanding dengan Kyai. Nampaknya sejauh ini, aku jarang atau bahkan tidak pernah mendengar bahwa Kyaiku dipanggil dengan ''Kyai'' atau Yi'' saja. Ya, Abah itulah panggilan akrab dari setiap oang yang mengenalnya. Bahwa aku justru mengenali Abah melalui kesederhanaannya, begitu ingat Abah atau mendengar Abah dari orang lain, hal pertama yang muncul dari benakku adalah kalau Abah itu sedehana. Bahkan sampai saat ni pun, aku belum menemu Kyai sesederhana Abah, dari mulai cara berpakaian, cara bertindak, bahkan cara berfikirpun sederhana. Aku sering menyaksikan sarung yang dipakai oleh Abah banyak lobang bekas sentuhan bara rokok, kaos oblong putih yang sudah berubah kecoklatan, sandal japit yang itu-itu saja. Yang demikian justru lebih bisa mengena untuk diambil sebagai cermin ke-teladanan ketimbang katakata motifasi, ya, aku lebih bisa mendapat pelajaran dari sikap dibanding pengajian. Sikap abah yang sederhana seringkali justru membuatku tersinggung, bukan apa-apa, aku yang hanya santri saja berpakaian selalu mewah, makan saja tidak bisa sederhana, begitu melihat Abah yang sedemikian rupa dengan penampilanku yang saat itu, secara tidak langsung Abah sudah menjewerku.
Ternyata, tidak hanya aku yang mempunyai pemikiran tentang Abah, hampir orang yang kenal beliau secara agak mendalam, mereka selalu punya anggapan yang nyaris sama sebagaimana aku. Aku jadi teringat dengan Sabda Nabi yang mengatakan bahwa Sebaik sesuatu adalah yang tengah-tengah. Aku memahami Hadis tersebut sudah melebur dalam diri Abah, bahwa sikap sederhana adalah bentuk lain dari pengamalan hadis tersebut, bahwa beragama pun dituntut untuk sederhana, sederhana dalam pengertian tidak melebih-lebihkan.
Untuk menemui tamu, Abah sering lebih mengambil sikap mendengarkan ketimbang bicara, saat itu pun, ketika malam senin aku sowan, sudah sekitar tiga jam aku tidak ditanyai apapun, posisiku yang menghadap beliau dari samping, berjarak setengah meter dari tempat Abah duduk, menjadikanku leluasa untuk merekam setiap apa yang disampaikan kepada ke tiga tamu yang, akhirnya kukenal mereka datang untuk permasalahan yang berbeda. Di antara perbincangan malam itu, tamu yang duduk paling dekat denganku menyampaikan keinginannya untuk bisa tahu keturunan dari siapa, ingin mengetahui nama-nama simbahnya sampai ke atas. Kata tamu yang berusia sekitar 50 tahun itu agar lakon tirakatnya berlangsung lancar, dan di antara syarat agar tirakatnya terpenuhi yaitu mengetahui simbahnya minimal tuju ke atas.
Abah tidak langsung mejawab, Abah diam agak lama dengan sesekali menyesap sukun kretek merahnya, tamu itu ternyata dibiarkan Abah, tidak dijawab, justru Abah bertanya kepada tamu lainnya tentang keperluannya, tamu di sebelahnya, yang posisiya di tengah itu berbadan gempal, gemuk. Bahwa dia sowan dalam rangka ingin meminta saran terkait mengapa perusahaan sapi-nya mengalami bangkrut sejak dua tahun terakhir. Abah menyimak dengan serius penuturan tamu gemuk itu, sekalikali Abah tersenyum, malam itu, aku mendapat pemandangan luar biasa, bukan hanya bibirnya, tapi seluruh wajah Abah tersenyum.
Dengan logat bahasa yang khas, Abah bicara pelah-pelan: Pertama, mengetahui nama simbah itu memang diperlukan, untuk sekadar tahu. Bahwa pencarian nama-nama simbah itu juga baik, tapi jangan terlalu ngotot. Kyai Masbuchin Gresik dulu juga meminta tolong aku untuk mencarikan nama-nama simbahnya. Sampai Kyai Masbukhin itu di rewangi tirakat 40 hari agar menemukan simbah-simbahnya. Tutur Abah dengan nada lembut, aku bilang kepadanya, susah-payah tirakat 40 hari kok hasilnya cuma tahu nama-nama simbahnya. Lanjut Abah.
Kalau menurutku itu tidak sebanding dengan tingkat rekosonya dalam berproses, terus kalau sudah tahu mau ngapain? Bahwa sekali lagi untuk mengetahui nama simbahnya itu baik, tapi mbok jangan ngoyo seperti itu. Penuturan Abah malam itu menggema di ruang sederhana. Aku kembali mendapati kesederhanaan beliau dalam menjawab serangkaian pertanyaan. Lebih lanjut lagi, Mengetahui nama-nama simbah tu lebih banyak mudhorotnya ketimbang manfaatnya. Dawuh beliau.
Saat itu, aku tersindir oleh jawaban Abah kepada tamu bahwa sejauh itu aku memang sedang berhasrat untuk mengetahu nama-nama simbahku, dan malam itu, kegelisahanku kembali dijawab Abah tanpa aku bertanya lebih dulu. Mudhorotnya itu banyak, potensi untuk menyombongkan diri lebih besar, begitu tahu simbah kita ternyata orang besar di zamannya, bisa jadi itu membuat kita bergantung kepadanya. Sekarang aku bertanya, ''kalau sudah tahu siapa nama simbah sampean, mau apa?''. Kulihat dengan wajah tertunduk, tamu itu sulit menggerakkan bibirnya untuk bicara, nampaknya tak ada jawaban yang tepat untuk sebuah pertanyaan yang dibuat se-retoris mungkin oleh Abah.
Aku jadi menyimpulkan bahwa keturunan dari siapapun itu tidak lantas menjadikannya hidup mulya dan masuk surga, ada banyak kisah yang bisa dibuat pelajaran. Nyatanya, Kan'an yang putranya nabi Nuh pun pada akhirnya masuk neraka, bisa kita lihat bagaimana piciknya kelakuan putra-putranya nabi Ya'qub yang menyengsarakan nabi Yusuf. Bahwa betapapun putranya seorang nabi, tidak menjamin segalanya. Bahkan nabi Ibrahim itu putra dari seorang Ayah yang menyembah berhala.
Jadi, dari keturunan siapa itu tidak menjadi barometer kesolehan seseorang, simbah-simbah kita yang baik itu tidak bisa menjadi tolak-ukur untuk kebaikan cucu-cucunya secara mutlak. Dari sekian kisah itu, di tambah dengan dawuh Abah, aku jadi sadar bahwa yang berperan untuk menentukan pada akhirnya khusnul khotimah atau tidak, itu adalah bukan soal keturunan siapa, tapi sepenuhnya dari Amal baik.
Menjadi bukti lagi bahwa di antara sekian pertanyaan di kubur kelak tidak ada pertanyaan yang menjurus soal keturunan. Malam itu benar-benar menjadi sebuah pengertian baru dari sowan tesebut, sementara itu sudah sekitar empat jam aku tanpa ditanya oleh Abah. Tapi dari setiap kata Abah itu mengandung cabang yang terhubung ke aku, bahwa aku juga menjadi bagian dari Mustahiqqul Khitob dawuh-dawuh Abah, sekali lagi, meski Abah tidak menanyaiku secara langsung. Kulihat, jam dinding yang menggantung di atas itu sudah menunjukkan hampir pukul setengah lima, berarti aku duduk disitu sudah lima jam lamanya, tanpa berkata sepatah pun.
Tiga tamu itu serentak pamit, mengingat waktu sudah mendekati subuh, dari wajah mereka terlihat kepuasan, nampaknya setelah itu mereka mengganti sikapnya masing-masing sesuai dawuh-dawuh Abah yang terasa tidak menggurui itu, terlihat dari senyum mereka yang tanpa beban ketika bersalaman dengan Abah itu membuatku paham bahwa sowannya mereka kepada Abah tidak siasia. Ke tiga tamu itu bangkit dan keluar, sementara aku masih duduk tanpa mengangkat wajah, setelah suasana benarbenar tenang, di mana di ruangan itu hanya aku dan Abah, baru beliau tanya kepadaku, ''piye piye Nang?'' Dengan perasaan yang bagaikan embun, aku bilang ''mboten sios Bah''. Kembali senyum di wajah Abah mengembang, menjadikan tubuhku kian hanyut.
Ya, persoalan yang semula hendak kusampaikan kepada Abah mendadak lenyap hanya karena memandang wajah Abah yang tersenyum, kegelisahan yang ingin kuadukan kepada Abah tibatiba sirna begitu mendengar dawuh Abah, tanpa aku berkata, tanpa aku bertanya. Senyumnya Abah secara tidak langsung menjadi jawaban paling moderat untuk orang segelisah aku, melihat geraknya Abah saja sudah cukup bagiku untuk jawaban sebagian besar permasalahan. Bahwa obat paling mujarab saat itu adalah dengan cara melihat Abah. cukup melihat dari kejauhan sudah sanggup membuatku tenang.
Selepas subuh, aku membuat kopi sendirian, di LP, jalur penghubung antara jalur gaza dan aula lantai 3, tepatnya bertempat di komplek C, aku menghadap ke tempat munculnya matahari, kusimpan bungkus rokok berikut isinya yang diberikan Abah itu di blebetan sarung, agar teman-teman tidak melihat, agar rokok pemberian Abah itu hanya aku yang menghabiskan, semata hanya ingin ngalap berkah, di samping itu, kebetulan aku sedang tidak punya uang untuk sekadar membeli sebatang rokok.
8 Mey 2013, Mesir


 Unknown
Unknown

.jpg)

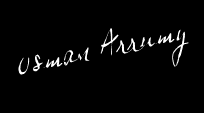









0 komentar